Akhir Pelarian
Anak laki-laki itu memandang ke arahku dengan tatapan heran. Lebih tepatnya, memandang ke bagian bawah tubuhku dengan mata yang dipenuhi oleh pertanyaan. Aku berusaha untuk tidak mengacuhkan pandangannya dan bergegas masuk ke ruang ganti yang aku harap sekarang sudah sepi, tas olahraga yang kuselempangkan di bahu kananku kugenggam dengan erat.
Aku telah bertekad bahwa mulai hari ini, aku akan melangkah kembali ke kehidupanku yang dulu, dimana lari dan waktu adalah segalanya bagiku, dimana semua orang mengenalku sebagai orang yang kuat, orang yang percaya diri, dan yang paling penting, orang yang bahagia.
Jantungku berdegup kencang begitu aku memasuki ruang ganti yang, aku amat sangat bersyukur, tidak diisi oleh seorangpun. Aku melesat ke ujung ruangan dan menemukan sebuah loker yang kosong. Dengan secepat mungkin kuganti bajuku ke pakaian olahraga.
Aku menarik nafas panjang begitu mencapai sebuah lapangan yang dikelilingi oleh lintasan lari yang dulu biasa aku gunakan bersama sahabat-sahabatku sesama anggota klub atletik. Seketika kenangan akan masa-masa itu yang seakan telah begitu lama pergi menghujam seluruh alam pikirku, membuat bulu kuduk di belakang leherku bergidik. Aku merasakan jantungku bergemuruh di dadaku.
Sanggupkah aku melakukannya?
Bukankah hati ini sudah cukup lelah untuk menerima kekecewaan lain?
... Pantaskah aku bahkan untuk berdiri di sini?
Aku melirik ke sekelilingku dan mendapati lima orang sedang berlari di lintasan tersebut, sepertinya sedang melakukan perlombaan informal atau hanya sekedar latihan. Mereka berlari dengan penuh semangat, bahkan kobaran keinginan mereka untuk menang terasa sangat membara bagiku. Kecepatan mereka pun sungguh mengagumkan, membuat kepercayaan diriku menurun secara drastis.
Melihat kelima orang tersebut, jantungku berdegup semakin keras. Aku terserang rasa panik dengan tiba-tiba. Bernafas yang biasanya kulakukan tanpa kesulitan sedikitpun sekarang terasa seperti tugas yang amat sangat berat dan menyita banyak sekali energi. Kurasakan keringat dingin mengucur di seluruh tubuhku, aku merasa lemas. Perutku seakan diisi oleh ribuan kupu-kupu atau apapun itu yang dapat membuat perutku terasa mual.
Aku berusaha mengatur nafasku. Kubiarkan tubuhku terdiam beberapa saat, mencoba menghilangkan rasa mual yang menyerangku. Kepalaku kubiarkan menunduk sehingga aku melihat lurus ke tanah. Entah berapa lama aku berdiri diam seperti itu di samping lapangan, namun sahutan seseorang dari kejauhan menyentakku dari keadaanku tersebut. Aku menoleh dan melihat seseorang menghampiriku. Tak kukenali sosok itu hingga akhirnya ia berdiri di depanku.
”Bene? Ini.. beneran lo, Ben? Ya ampun, sumpah lama banget gue ngga ngeliat lo! Satu setengah tahun ada kali ya?”
Aku menatap wajahnya. Ah, itu Tommy, salah satu temanku di klub atletik.
“Tommy. Iya, udah lama banget gue ga mampir,” balasku dengan suara yang agak datar. Aku berusaha untuk bersikap tenang. Tommy menyengir mendengar jawaban yang kulontarkan tadi.
“Mau olahraga ya? Kaki lo gimana? Udah terbiasa sekarang?”
Aku memaksakan sebuah cengiran. Palsu. Aku merasa palsu. “Yaa, lumayan lah. Gue udah sering terapi juga. Minggu lalu dokter gue juga udah bilang kalo gue udah bisa balik lagi ke lapangan.”
Tommy menatapku aneh sebelum tersenyum agak risih.
“Lo.. Lo mau balik ke lapangan?”
Aku mengangguk sedikit. Tiba-tiba aku merasa ragu. Ada aura skeptis memancar di sekeliling Tommy.
“Lo jangan maksain diri ya Ben! Maksud gue, lo harus lihat situasi lo dulu. Apalagi dengan kondisi kaki lo yang kaya’ gitu, lebih baik lo lari santai-santai aja. Oke?” katanya sambil menepuk pundakku. Aku terkejut dengan kata-katanya, namun dengan sekuat tenaga aku tetap memberikannya sebuah senyuman. Senyuman getir. Ia balik menyengir dengan canggung, sebelum menatap ke arah kelompoknya sesaat. Aku mengikuti arah pandangannya dan melihat seorang bapak yang sangat kukenal karena dulu ia pernah menjadi pelatihku mengangkat tangannya dan membentuk gerakan memanggil ke arah kami. Mungkin lebih tepatnya, ke arah Tommy.
“Gue tinggal dulu, oke? Pak Broto udah manggil gue lagi tu. Ingat, lo jangan maksain diri ya! Santai aja!” Dengan sebuah lambaian, dia pergi meninggalkanku.
Aku merasakan diriku jatuh terpuruk. Kepercayaan diri yang sudah kutumpuk tinggi-tinggi selama aku terapi di rumah sakit tiba-tiba runtuh karena percakapan barusan. Sebegitu menyedihkankah aku sehingga orang yang dulu selalu tertinggal di belakangku kini menganggapku tidak mampu lagi untuk ikut lari bersama dengan yang lain?
Aku menatap lemah ke arah kakiku. Kaki kananku. Seketika ingatan satu setengah tahun yang lalu, ingatan akan hari itu kembali, hari dimana segalanya berubah.
**
Aku berlari di tengah kegelapan yang membutakan mata, ingin dengan segera mencapai rumahku yang hanya tinggal beberapa blok lagi. Angin dingin menerpa wajahku namun tidak kuhiraukan. Sambil berlari, kubiarkan pandanganku beralih ke sekeliling. Toko-toko yang berderet di sisi trotoir kebanyakan sudah berhenti dari aktivitas berjualannya, sehingga hanya lampu-lampu redup yang ada di sisi lainnya yang menjadi penerangan di malam yang tidak dihiasi bintang itu.
Hanya satu blok lagi, dan aku akan tiba di tempat tidurku yang hangat. Sebelumnya aku akan berendam dan melemaskan otot-otot yang sudah terlalu lelah karena latihan tadi. Aku tersenyum membayangkan rencanaku begitu aku sampai di rumah nanti.
Namun, sepertinya harapanku itu hanya dapat menjadi sebuah harapan kosong, karena tiba-tiba, dari arah belakang, aku mendengar suara decitan ban yang beradu dengan jalan. Aku berbalik menoleh dan melihat sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi ke arahku. Mobil itu bergerak tanpa kendali dan keluar dari jalurnya bagaikan dikejar oleh sesuatu yang amat mengerikan. Begitu aku memahami apa yang terjadi, aku sudah tergeletak di pinggir jalan, bersimbah darah. Tubuhku terasa sangat kaku. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sedikitpun.
Yang terakhir kali kulihat adalah kerumunan orang-orang yang panik dan berteriak sebelum akhirnya kegelapan datang menghampiri.
Ketika aku tersadar, aku tidak merasakan sakit apapun. Aku bahkan benar-benar tidak merasakan apapun di bagian bawah tubuhku. Aku menoleh dan melihat ibu berdiri dengan wajah yang sedih, jelas sekali terdapat jejak bekas air mata di kedua pipinya. Pada awalnya aku merasa heran, namun begitu aku melihat ibu kembali menangis tercekat, aku menjadi takut. Kurasakan paranoia yang luar biasa menghujamku.
Apa yang terjadi?
K-Kenapa aku tak bisa merasakan apapun?
Aku berusaha bangkit walau ibu menahanku dengan sekuat tenaga. Kuraih ujung selimut yang menutupi badanku dan kusibakkan selimut itu dengan kasar.
Apa yang kulihat membuatku menjerit dengan sangat kencang bagaikan jeritan yang bukan berasal dari manusia.
Di tempat yang seharusnya merupakan lutut dan betis kananku, kini telah lenyap dan diganti dengan balutan perban dengan sedikit noda merah yang seakan dengan sinis memvonis diriku sebagai seorang cacat seumur hidup.

**
“Ma, kaki kanan kakak itu aneh!”
Sebuah seruan yang melengking membuatku tersadar dari lamunanku. Dengan spontan aku menoleh ke asal suara tersebut. Di sebuah kursi di pinggir lapangan, kulihat seorang anak sedang melihat ke arahku sambil merengut dan memegangi tangan ibunya. Aku mengenali anak itu sebagai anak yang memandangku dengan aneh ketika aku tiba di lapangan olahraga ini. Rupanya dia masih penasaran dengan kakiku.
Ibu dari anak itu memandangku seolah-olah ingin meminta maaf. Ia melihat ke anaknya sesaat sebelum kembali mengalihkan pandangannya padaku. Aku hanya terdiam.
Sang ibu tiba-tiba menarik anaknya dan bergerak ke arahku. Anaknya terkejut, dan berusaha untuk melawan walau agak sia-sia. Ia takut padaku, sepertinya.
“Tolong maafkan perkataan anak saya tadi, dia memang selalu penasaran,” ujar sang Ibu begitu mereka mencapaiku, anaknya bersembunyi di belakang figurnya. Aku hanya tertawa risih dan mengatakan padanya untuk tidak khawatir, karena aku tidak mempermasalahkannya. Kualihkan pandanganku pada anak kecil itu. Dia masih bersembunyi, namun berusaha untuk melirik ke arahku.
“Ayo, Rais, minta maaf sama kakaknya!” ibunya mendorong anak laki-laki tersebut untuk keluar dari persembunyiannya.
“M-maaf, kak..” ujarnya pelan. Aku tersenyum lebar dan membungkuk agar mataku selevel dengannya. “Nggak apa-apa. Kamu mau lihat kakak lari?”
Mendengar pertanyaanku, mata anak itu langsung berbinar. Dia memandang kakiku sebelum kembali memandang tepat ke mataku.
“Bisa lari dengan kaki itu?” tanyanya dengan semangat. Aku terkejut. Dengan sedikit ragu, aku berkata, “Umm, mungkin. Kakak harap begitu.”
“Bisa ngeluarin turbo speed?“ aku tertawa kecil mendengar pertanyaannya. Moodku membaik. “Eh, yaaa, mungkin?”
Binar matanya semakin bertambah.
”Kalau gitu, kakak pasti bisa ngalahin kakak-kakak disana!” ujarnya mantap. ”Jangan kalah, kak! Jangan nyerah! Kakak pasti bisa!” anak itu berkata dengan semangat, tangannya diancungkan ke atas. Aku terdiam dan hanya dapat berdiri memaku. Ibunya tersenyum di sisi anak laki-laki itu, seakan bangga dengan ucapan yang dilontarkan oleh anaknya. Mereka pamit untuk kembali duduk di podium penonton, anak laki-laki itu melambai ke arahku.
Aku merasakan hatiku tersentak dengan kuat ketika mendengar semangat yang diberikan anak laki-laki itu. Entah kenapa, hanya beberapa kalimat dari seorang anak kecil yang mungkin sama sekali tidak memahami bagaimana rasanya memiliki sebuah prosthesis sebagai pengganti kaki mengobarkan lagi tekadku untuk kembali berlari. Untuk kembali hidup. Aku mengerlingkan pandanganku sesaat pada anak laki-laki yang kini telah duduk di podium itu, seakan mengatakan ’Serahkan saja padaku!’ sebelum memantapkan pijakan kakiku di tanah. Kuukir seulas senyum di bibirku.
Aku pasti bisa!
 Satu tahun berlalu setelah aku menapakkan kakiku kembali di jalur lari. Aku melangkah menaiki tangga di tengah kerumunan orang-orang yang berseru dengan kencangnya, beberapa menepuk dan menyorakiku, aku membalas mereka dengan sebuah cengiran yang sangat lebar. Gaungan nama-nama juara lomba atletik yang baru saja diumumkan masih membekas di dadaku.
Satu tahun berlalu setelah aku menapakkan kakiku kembali di jalur lari. Aku melangkah menaiki tangga di tengah kerumunan orang-orang yang berseru dengan kencangnya, beberapa menepuk dan menyorakiku, aku membalas mereka dengan sebuah cengiran yang sangat lebar. Gaungan nama-nama juara lomba atletik yang baru saja diumumkan masih membekas di dadaku.
Peringkat kedua, sprint 400 meter pria, Bene Trias.
Aku tersenyum dengan puas.
Aku telah bertekad bahwa mulai hari ini, aku akan melangkah kembali ke kehidupanku yang dulu, dimana lari dan waktu adalah segalanya bagiku, dimana semua orang mengenalku sebagai orang yang kuat, orang yang percaya diri, dan yang paling penting, orang yang bahagia.
Jantungku berdegup kencang begitu aku memasuki ruang ganti yang, aku amat sangat bersyukur, tidak diisi oleh seorangpun. Aku melesat ke ujung ruangan dan menemukan sebuah loker yang kosong. Dengan secepat mungkin kuganti bajuku ke pakaian olahraga.
Aku menarik nafas panjang begitu mencapai sebuah lapangan yang dikelilingi oleh lintasan lari yang dulu biasa aku gunakan bersama sahabat-sahabatku sesama anggota klub atletik. Seketika kenangan akan masa-masa itu yang seakan telah begitu lama pergi menghujam seluruh alam pikirku, membuat bulu kuduk di belakang leherku bergidik. Aku merasakan jantungku bergemuruh di dadaku.
Sanggupkah aku melakukannya?
Bukankah hati ini sudah cukup lelah untuk menerima kekecewaan lain?
... Pantaskah aku bahkan untuk berdiri di sini?
Aku melirik ke sekelilingku dan mendapati lima orang sedang berlari di lintasan tersebut, sepertinya sedang melakukan perlombaan informal atau hanya sekedar latihan. Mereka berlari dengan penuh semangat, bahkan kobaran keinginan mereka untuk menang terasa sangat membara bagiku. Kecepatan mereka pun sungguh mengagumkan, membuat kepercayaan diriku menurun secara drastis.
Melihat kelima orang tersebut, jantungku berdegup semakin keras. Aku terserang rasa panik dengan tiba-tiba. Bernafas yang biasanya kulakukan tanpa kesulitan sedikitpun sekarang terasa seperti tugas yang amat sangat berat dan menyita banyak sekali energi. Kurasakan keringat dingin mengucur di seluruh tubuhku, aku merasa lemas. Perutku seakan diisi oleh ribuan kupu-kupu atau apapun itu yang dapat membuat perutku terasa mual.
Aku berusaha mengatur nafasku. Kubiarkan tubuhku terdiam beberapa saat, mencoba menghilangkan rasa mual yang menyerangku. Kepalaku kubiarkan menunduk sehingga aku melihat lurus ke tanah. Entah berapa lama aku berdiri diam seperti itu di samping lapangan, namun sahutan seseorang dari kejauhan menyentakku dari keadaanku tersebut. Aku menoleh dan melihat seseorang menghampiriku. Tak kukenali sosok itu hingga akhirnya ia berdiri di depanku.
”Bene? Ini.. beneran lo, Ben? Ya ampun, sumpah lama banget gue ngga ngeliat lo! Satu setengah tahun ada kali ya?”
Aku menatap wajahnya. Ah, itu Tommy, salah satu temanku di klub atletik.
“Tommy. Iya, udah lama banget gue ga mampir,” balasku dengan suara yang agak datar. Aku berusaha untuk bersikap tenang. Tommy menyengir mendengar jawaban yang kulontarkan tadi.
“Mau olahraga ya? Kaki lo gimana? Udah terbiasa sekarang?”
Aku memaksakan sebuah cengiran. Palsu. Aku merasa palsu. “Yaa, lumayan lah. Gue udah sering terapi juga. Minggu lalu dokter gue juga udah bilang kalo gue udah bisa balik lagi ke lapangan.”
Tommy menatapku aneh sebelum tersenyum agak risih.
“Lo.. Lo mau balik ke lapangan?”
Aku mengangguk sedikit. Tiba-tiba aku merasa ragu. Ada aura skeptis memancar di sekeliling Tommy.
“Lo jangan maksain diri ya Ben! Maksud gue, lo harus lihat situasi lo dulu. Apalagi dengan kondisi kaki lo yang kaya’ gitu, lebih baik lo lari santai-santai aja. Oke?” katanya sambil menepuk pundakku. Aku terkejut dengan kata-katanya, namun dengan sekuat tenaga aku tetap memberikannya sebuah senyuman. Senyuman getir. Ia balik menyengir dengan canggung, sebelum menatap ke arah kelompoknya sesaat. Aku mengikuti arah pandangannya dan melihat seorang bapak yang sangat kukenal karena dulu ia pernah menjadi pelatihku mengangkat tangannya dan membentuk gerakan memanggil ke arah kami. Mungkin lebih tepatnya, ke arah Tommy.
“Gue tinggal dulu, oke? Pak Broto udah manggil gue lagi tu. Ingat, lo jangan maksain diri ya! Santai aja!” Dengan sebuah lambaian, dia pergi meninggalkanku.
Aku merasakan diriku jatuh terpuruk. Kepercayaan diri yang sudah kutumpuk tinggi-tinggi selama aku terapi di rumah sakit tiba-tiba runtuh karena percakapan barusan. Sebegitu menyedihkankah aku sehingga orang yang dulu selalu tertinggal di belakangku kini menganggapku tidak mampu lagi untuk ikut lari bersama dengan yang lain?
Aku menatap lemah ke arah kakiku. Kaki kananku. Seketika ingatan satu setengah tahun yang lalu, ingatan akan hari itu kembali, hari dimana segalanya berubah.
**
Aku berlari di tengah kegelapan yang membutakan mata, ingin dengan segera mencapai rumahku yang hanya tinggal beberapa blok lagi. Angin dingin menerpa wajahku namun tidak kuhiraukan. Sambil berlari, kubiarkan pandanganku beralih ke sekeliling. Toko-toko yang berderet di sisi trotoir kebanyakan sudah berhenti dari aktivitas berjualannya, sehingga hanya lampu-lampu redup yang ada di sisi lainnya yang menjadi penerangan di malam yang tidak dihiasi bintang itu.
Hanya satu blok lagi, dan aku akan tiba di tempat tidurku yang hangat. Sebelumnya aku akan berendam dan melemaskan otot-otot yang sudah terlalu lelah karena latihan tadi. Aku tersenyum membayangkan rencanaku begitu aku sampai di rumah nanti.
Namun, sepertinya harapanku itu hanya dapat menjadi sebuah harapan kosong, karena tiba-tiba, dari arah belakang, aku mendengar suara decitan ban yang beradu dengan jalan. Aku berbalik menoleh dan melihat sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi ke arahku. Mobil itu bergerak tanpa kendali dan keluar dari jalurnya bagaikan dikejar oleh sesuatu yang amat mengerikan. Begitu aku memahami apa yang terjadi, aku sudah tergeletak di pinggir jalan, bersimbah darah. Tubuhku terasa sangat kaku. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sedikitpun.
Yang terakhir kali kulihat adalah kerumunan orang-orang yang panik dan berteriak sebelum akhirnya kegelapan datang menghampiri.
Ketika aku tersadar, aku tidak merasakan sakit apapun. Aku bahkan benar-benar tidak merasakan apapun di bagian bawah tubuhku. Aku menoleh dan melihat ibu berdiri dengan wajah yang sedih, jelas sekali terdapat jejak bekas air mata di kedua pipinya. Pada awalnya aku merasa heran, namun begitu aku melihat ibu kembali menangis tercekat, aku menjadi takut. Kurasakan paranoia yang luar biasa menghujamku.
Apa yang terjadi?
K-Kenapa aku tak bisa merasakan apapun?
Aku berusaha bangkit walau ibu menahanku dengan sekuat tenaga. Kuraih ujung selimut yang menutupi badanku dan kusibakkan selimut itu dengan kasar.
Apa yang kulihat membuatku menjerit dengan sangat kencang bagaikan jeritan yang bukan berasal dari manusia.
Di tempat yang seharusnya merupakan lutut dan betis kananku, kini telah lenyap dan diganti dengan balutan perban dengan sedikit noda merah yang seakan dengan sinis memvonis diriku sebagai seorang cacat seumur hidup.

**
“Ma, kaki kanan kakak itu aneh!”
Sebuah seruan yang melengking membuatku tersadar dari lamunanku. Dengan spontan aku menoleh ke asal suara tersebut. Di sebuah kursi di pinggir lapangan, kulihat seorang anak sedang melihat ke arahku sambil merengut dan memegangi tangan ibunya. Aku mengenali anak itu sebagai anak yang memandangku dengan aneh ketika aku tiba di lapangan olahraga ini. Rupanya dia masih penasaran dengan kakiku.
Ibu dari anak itu memandangku seolah-olah ingin meminta maaf. Ia melihat ke anaknya sesaat sebelum kembali mengalihkan pandangannya padaku. Aku hanya terdiam.
Sang ibu tiba-tiba menarik anaknya dan bergerak ke arahku. Anaknya terkejut, dan berusaha untuk melawan walau agak sia-sia. Ia takut padaku, sepertinya.
“Tolong maafkan perkataan anak saya tadi, dia memang selalu penasaran,” ujar sang Ibu begitu mereka mencapaiku, anaknya bersembunyi di belakang figurnya. Aku hanya tertawa risih dan mengatakan padanya untuk tidak khawatir, karena aku tidak mempermasalahkannya. Kualihkan pandanganku pada anak kecil itu. Dia masih bersembunyi, namun berusaha untuk melirik ke arahku.
“Ayo, Rais, minta maaf sama kakaknya!” ibunya mendorong anak laki-laki tersebut untuk keluar dari persembunyiannya.
“M-maaf, kak..” ujarnya pelan. Aku tersenyum lebar dan membungkuk agar mataku selevel dengannya. “Nggak apa-apa. Kamu mau lihat kakak lari?”
Mendengar pertanyaanku, mata anak itu langsung berbinar. Dia memandang kakiku sebelum kembali memandang tepat ke mataku.
“Bisa lari dengan kaki itu?” tanyanya dengan semangat. Aku terkejut. Dengan sedikit ragu, aku berkata, “Umm, mungkin. Kakak harap begitu.”
“Bisa ngeluarin turbo speed?“ aku tertawa kecil mendengar pertanyaannya. Moodku membaik. “Eh, yaaa, mungkin?”
Binar matanya semakin bertambah.
”Kalau gitu, kakak pasti bisa ngalahin kakak-kakak disana!” ujarnya mantap. ”Jangan kalah, kak! Jangan nyerah! Kakak pasti bisa!” anak itu berkata dengan semangat, tangannya diancungkan ke atas. Aku terdiam dan hanya dapat berdiri memaku. Ibunya tersenyum di sisi anak laki-laki itu, seakan bangga dengan ucapan yang dilontarkan oleh anaknya. Mereka pamit untuk kembali duduk di podium penonton, anak laki-laki itu melambai ke arahku.
Aku merasakan hatiku tersentak dengan kuat ketika mendengar semangat yang diberikan anak laki-laki itu. Entah kenapa, hanya beberapa kalimat dari seorang anak kecil yang mungkin sama sekali tidak memahami bagaimana rasanya memiliki sebuah prosthesis sebagai pengganti kaki mengobarkan lagi tekadku untuk kembali berlari. Untuk kembali hidup. Aku mengerlingkan pandanganku sesaat pada anak laki-laki yang kini telah duduk di podium itu, seakan mengatakan ’Serahkan saja padaku!’ sebelum memantapkan pijakan kakiku di tanah. Kuukir seulas senyum di bibirku.
Aku pasti bisa!
=*=*=*=*=
 Satu tahun berlalu setelah aku menapakkan kakiku kembali di jalur lari. Aku melangkah menaiki tangga di tengah kerumunan orang-orang yang berseru dengan kencangnya, beberapa menepuk dan menyorakiku, aku membalas mereka dengan sebuah cengiran yang sangat lebar. Gaungan nama-nama juara lomba atletik yang baru saja diumumkan masih membekas di dadaku.
Satu tahun berlalu setelah aku menapakkan kakiku kembali di jalur lari. Aku melangkah menaiki tangga di tengah kerumunan orang-orang yang berseru dengan kencangnya, beberapa menepuk dan menyorakiku, aku membalas mereka dengan sebuah cengiran yang sangat lebar. Gaungan nama-nama juara lomba atletik yang baru saja diumumkan masih membekas di dadaku.Peringkat kedua, sprint 400 meter pria, Bene Trias.
Aku tersenyum dengan puas.
(Bandung, 13 Oktober 2009)
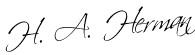







10 comments:
great. keep on writing,,,
nice =))...
jd serasa bc cerpen terjemahan...
karena sring bc tulisan hanny yg b.ing kli yaa,..
hehehe...
bagus han ceritanya..like this =)
aku selalu suka cerpen ini, hani :)
terima kasih untuk apresiasinya kk bagus, emje, sari, ayu! hehe.. tunggu postingan cerita aku selanjutnya yaaa.. :D
bagus cerpennya. aku suka makna ceritanya.. =)
bagus haaan..
mau liat yang lain..
:)
makasi banyak syndi dan ichaaa~ keep reading my stories, oke? hehehe.
good honey, minat klo di tekuni bisa jadi bakat dan lama2 siapa tau jadi jalan hidup, keep writing honey ^^
makasi feri,
doain bisa tekun menulis yaa, aku suka menunda2 sih orangnya.
i'm a procrastinate writer after all. hahahah.
Post a Comment